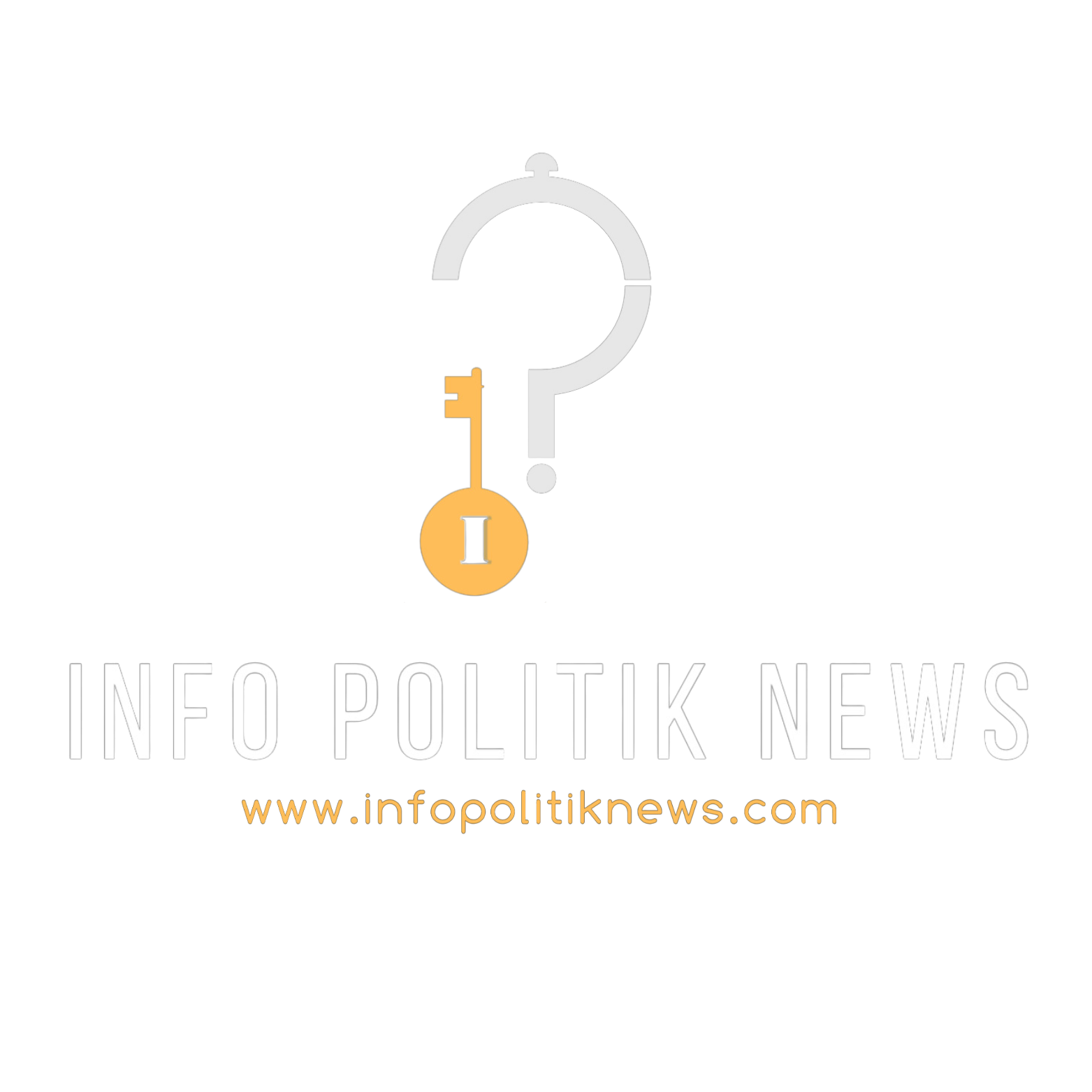Di dalam otak mereka
Hanyalah kekuasaan
Di dalam hati mereka
Tak ada kepuasan
Di dalam cara mereka
Terpampang kedzaliman
Di dalam harap mereka
Cahaya kemenangan
LIRIK lagu “Gelap Gempita” dari band Sukatani seakan menjadi jawaban keresahan anak-anak muda kita sekarang ini.
Para penggangguran korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), para pencari kerja yang semakin sulit menemukan lowongan kerja hingga korban nasib penghasilan berkurang atas nama efisiensi anggaran.
Rasa putus asa dan apatis terhadap kebobrokan para pejabat dan yang diberi amanah mengelola kekayaan negeri seakan sudah mencapai titik kulminasi ketika kasus Pertamina Patra Niaga terkuak ke publik.
Kasus rasuah “super gemoy maksimal jumbo” yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga diungkap oleh Kejaksaan Agung. Nilai kerugian negaranya diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023 saja.
Akibat praktik kotor yang berlangsung dari 2018 hingga 2023, total estimasi kerugian mencapai Rp 968,5 triliun (Kompas.id, 04 Maret 2025).
Skandal megakorupsi terjadi dalam kurun waktu cukup lama serta dampaknya begitu besar bagi pemerintah dan masyarakat.
Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang bertanggung jawab atas BUMN.
Masyarakat sekarang akan berpikir dua kali jika hendak mengisi bahan bakar kendaraan ke SPBU Pertamina. Lebih baik membayar lebih mahal di SPBU swasta asal tidak “dikadalin”.
Kasus ini menjadi salah satu skandal paling besar dalam sejarah industri migas di Indonesia, tercermin dari angka kerugian yang begitu fantastis.
Pelakunya dari waktu ke waktu juga melibatkan yang “itu-itu saja”. Semula dari sang ayah yang tersangkut di Petral, kini mewarisi ke sang anak lewat Pertamina Patra Niaga.
Antara “blending” dan “Oplos”
Saat pemberitaan kasus megakorupsi pertamina menyebar luas dalam beberapa platform media massa dan media digital, istilah blending (dalam Bahasa Inggris) atau oplos (dalam Bahasa Jawa) BBM mencuat di tengah dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, sub holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.
Dua istilah memicu tafsir beragam dari publik. Bagi Pertamina, proses blending BBM bertujuan memperbaiki kualitas BBM agar sesuai standar yang dibutuhkan kendaraan. Tindakan demikian memang diperlukan dan wajar dalam industri migas.
Proses ini sering dilakukan di kilang minyak atau terminal penyimpanan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar nilai oktan yang tepat.
Namun, nampak berbeda bagi publik atau konsumen perihal istilah tersebut. Dalam perspektif demikian, penting melihat bagaimana penggunaan komunikasi yang tepat dan berdasar fakta perlu digunakan kembali untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan publik pada Pertamina.
Dualisme antara “blending” dan “oplos” saya sebut sebagai komunikasi asap. Sebuah istilah untuk menggambarkan bagaimana manipulasi informasi dilakukan untuk membentuk opini publik demi kepentingan tertentu.
Istilah ini menunjuk pada komunikasi yang tidak transparan dan membingungkan. Bagaikan asap yang menyelimuti pandangan, sehingga publik kesulitan membedakan fakta dari kebohongan dalam konteks korupsi.
Dalam kasus rasuah Pertamina Patra Niaga, fenomena komunikasi asap dapat dilihat dari penggunaan dua istilah yang membingungkan, yaitu “mengoplos” dan “blending”.
Sebagian pemberitaan tentang kasus ini menggunakan istilah “oplos-mengoplos” mengacu pada pernyataan Kejaksaan Agung terhadap modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dalam pengelolaan minyak dan produksi kilang, di mana pertalite diolah menjadi pertamax.
Beberapa media menggunakan istilah “blending”, mengacu dari cara para tersangka yang diduga membeli pertalite untuk di-blending menjadi pertamax. Hasil blending tersebut kemudian dijual dengan setara harga pertamaks.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “mengoplos” sebagai aktivitas mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan lain sehingga kadar keasliannya menurun.
Sementara itu, dalam Oxford Dictionary, istilah “blending” berasal dari kata “blend”, yang artinya mencampurkan dua atau lebih zat menjadi satu.
Meskipun antara istilah mengoplos dan blending memiliki substansi makna yang sama, pihak Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa tidak ada praktik pengoplosan pertamax.
Pertamina malah memastikan bahwa kualitas pertamax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu dengan Research Octane Number (RON) 92.
Menurut pernyataan Pertamina, pertamax tetap menggunakan RON 92, hanya ditambahkan aditif pewarna tanpa mengurangi kualitasnya.
Dialektika antara pengoplosan dan blending di hadapan publik tentu saja semakin memperburuk citra serta reputasi Pertamina sebagai perusahaan milik pemerintah.
Publik mulai merasa bahwa pertamax yang mereka beli selama ini tidak berbeda jauh kualitasnya dengan pertalite.
Bahkan pemahaman masyarakat terbaru pascakasus tersebut mencuat, begitu menyesali dengan anggapan yang selama ini, yakni pertamax mampu meningkatkan performa mesin kendaraan.
Selama ini membeli pertamax yang lebih mahal harganya, ternyata identik dengan membeli pertalite tanpa antre.
Dengan adanya pengalihan pembelian BBM ke SPBU swasta, reputasi Pertamina semakin tergerus. Publik dihadapkan pada informasi yang membingungkan; istilah “mengoplos” memiliki konotasi negatif, sementara istilah “blending” yang digunakan oleh Pertamina justru tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, yang membuat mereka semakin bingung.
Awas penyesatan informasi
Fenomena komunikasi yang ambigu muncul akibat pengaburan istilah atau bahkan penyembunyian informasi yang esensial.
Berbagai pihak memanfaatkan media untuk membingkai opini publik, berusaha memosisikan kebocoran dana (korupsi) sebagai kesalahan administrasi, bukan sebagai masalah sistemik.
Istilah-istilah rumit yang digunakan dapat memanipulasi pemahaman masyarakat tentang fakta yang sebenarnya.
Kolaborasi ini menciptakan “asap informasi” yang menyulitkan publik untuk membedakan antara fakta dan manipulasi.
Dari sudut pandang komunikasi, wacana tentang korupsi bisa dibingkai melalui media untuk menyebarluaskan informasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Misalnya, Kejaksaan Agung membingkai berita terkait korupsi di Pertamina Patra Niaga dengan istilah pengoplosan BBM dari RON 90 (pertalite) menjadi RON 92 (pertamax).
Masyarakat cenderung menerima bingkai berita pertama yang mereka tangkap dan lebih terpatri dalam ingatan mereka.
Begitu informasi disampaikan kepada publik, ia telah menjadi milik masyarakat, sehingga pesan yang diterima tidak bisa ditarik kembali.
Sementara itu, framing media dengan istilah blending, meskipun mengandung kebenaran, sulit diterima masyarakat karena mereka lebih dulu menganggap pesan pertama sebagai kebenaran.
Teori resepsi dari Stuart Hall menunjukkan bahwa ada tiga cara khalayak dalam menerima pesan.
Pertama, pada kategori. Informasi mengenai praktik korupsi Pertamina Patra Niaga dengan proses pengoplosan diterima begitu saja tanpa proses seleksi.
Publik dengan karakteristik ini sulit menerima framing berita kedua yang berusaha mengklarifikasi berita pertama. Mereka cenderung mengabaikan berita kedua, sehingga berita pertama tetap dianggap sebagai kebenaran.
Kedua, pada kategori selectivity. Khalayak dengan karakteristik ini bersikap lebih selektif dalam menerima informasi.
Mereka cenderung memilih berita yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka, dapat memfilter informasi, dan akhirnya memutuskan untuk lebih percaya pada berita tentang pengoplosan atau blending.
Ketiga, pada kategori opposition. Khalayak ini biasanya menolak informasi apa pun yang disajikan oleh media. Mereka cenderung acuh tak acuh terhadap pemberitaan, bahkan ada kecenderungan untuk melawan informasi tersebut.
Dari kasus Pertamina Patra Niaga ini akhirnya kita bisa melihat pengungkapan kasus rasuah tidak semata teknis hukum saja, tetapi menjadi “koentji” adalah penanganan aspek komunikasi.
Publik harus memahami konteks waktu dan struktur tanggungjawab dalam kasus ini. Publik harus mendapat literasi kasus Pertamina Patra Niaga bahwa “tempus delicti” terjadi pada periode 2018 hingga 2023. Dari titik tolak ini kita bisa melihat pihak-pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya.
Siapa presiden-nya, siapa menteri BUMN-nya, siapa menteri ESDM-nya, siapa direktur Pertamina-nya, siapa direktur Pertamina Patra Niaga-nya, termasuk siapa saja komisarisnya ketika itu.
Maling-maling kecil kecil dihakimi
Maling-maling besar dilindungi
Di manakah letak keadilan
Jika masih memandang golongan
Yang kuat selalu berkuasa
Yang lemah makin merana
(Lirik lagu “Hukum Rimba” oleh Sabill 86)
Ditulis oleh:
Dr. Ari Junaedi
Doktor Komunikasi Politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Harapan Setara Pertamax, Kenyataan Setara Pertalite”
(Kompas.com – 08/03/2025, 06:15 WIB)