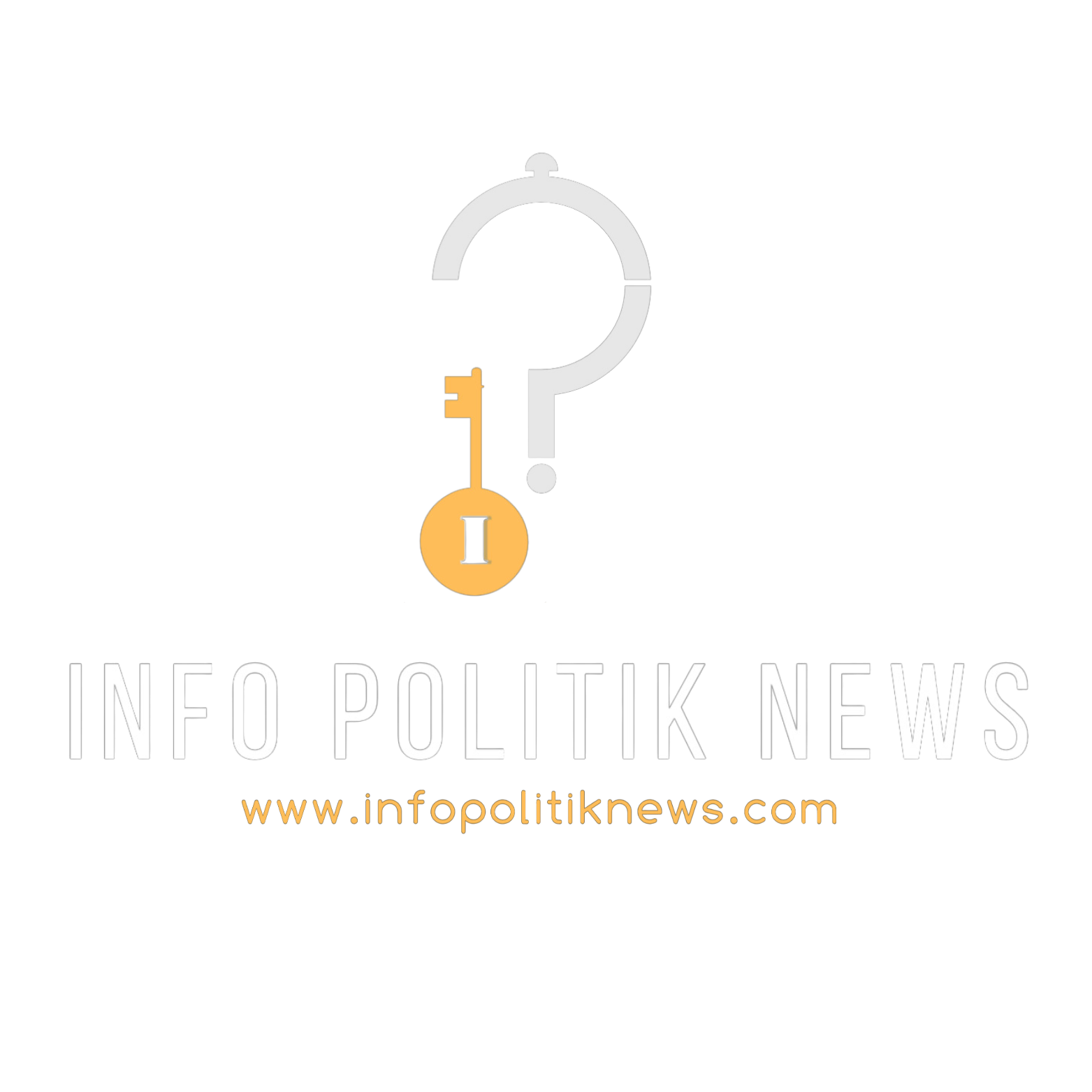Oleh: Fathimah Sulistyowati Sigit
Dosen dan Ketua Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap kebijakan publik Indonesia, sekaligus menandai realisasi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Implementasinya yang telah menjangkau jutaan siswa di berbagai pelosok negeri sejatinya membawa harapan baru untuk perbaikan status gizi anak-anak Indonesia.
Meski demikian, terdapat sejumlah isu kritis yang perlu segera diatasi agar keberlanjutan, efektivitas, dan dampak jangka panjang program ini terjaga.
Standar Keamanan Pangan
Terjadinya kasus infeksi saluran pencernaan dan keracunan makanan di sejumlah sekolah penerima manfaat MBG—termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Bandung Barat pekan lalu—menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat.
Penerapan prinsip manajemen sistem penyelenggaraan makanan yang andal serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) harus dilakukan seragam di semua unit, mencakup seluruh rantai proses: dari pemilihan dan penyimpanan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian.
Monitoring dan evaluasi rutin perlu diperketat, menjamin penerapan prinsip quality assurance dan quality control. Muatan pengetahuan mengenai mutu dan keamanan pangan juga harus diperkuat dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang melatih calon Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini, fokus SPPI masih pada kepemimpinan manajerial dan logistik, padahal banyak peserta tanpa latar belakang gizi atau kesehatan.
Seluruh SPPG juga patut diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga kini, baru 34 dari 8.583 SPPG yang memiliki standardisasi ini. Kenyataan bahwa sejumlah SPPG belum pernah mendapat kunjungan monitoring dan evaluasi rutin dari Badan Gizi Nasional juga menunjukkan celah pengawasan. Jangan sampai SPPG baru diaudit ketika kasus keracunan massal terjadi dan menimpa ribuan siswa.
Regulasi Pengelolaan Sisa Makanan
Terkait laporan media tentang makanan yang terbuang di sekolah-sekolah, penguatan regulasi pengelolaan sisa makanan menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data SIPSN KLHK tahun 2024, sampah makanan telah mencapai sekitar 40% dari total timbulan sampah nasional, bahkan sebelum program MBG berjalan. Dengan asumsi timbulan 50–100 gram per siswa per hari, potensi sampah makanan bisa mencapai 2.400 ton per hari atau 624 ribu ton per tahun.
Diperlukan strategi komprehensif: pengumpulan terpusat sisa makanan untuk didaur ulang, redistribusi makanan berlebih ke komunitas sekitar, serta analisis penyebab rendahnya penerimaan makanan siswa.
Jika penyebabnya karena makanan tidak menarik, melibatkan siswa untuk memberikan umpan balik dalam penyusunan menu—misalnya dengan uji hedonik—dapat meningkatkan penerimaan makanan dan mengurangi sampah makanan.
Fokus Wilayah Target
Meski MBG menargetkan menjangkau 82,9 juta siswa penerima pada akhir 2025, pemfokusan pada wilayah dengan prevalensi gizi kurang (wasting dan stunting) tertinggi sebaiknya dipertimbangkan agar alokasi sumber daya lebih tepat sasaran.
Anggaran negara sebesar Rp171 triliun di 2025 untuk MBG, dan Rp335 triliun di 2026, memaksa negara melakukan efisiensi di berbagai sektor krusial.
Dengan fokus wilayah target, alokasi anggaran makan per anak yang saat ini hanya Rp10.000 dapat ditingkatkan sehingga kualitas makanan lebih baik, tidak sekadar kuantitas. Porsi makanan pun dapat disesuaikan agar memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Jika wilayah percontohan dipilih, intervensi dapat diperluas ke kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita—mengingat isu kekurangan gizi seperti stunting merupakan persoalan lintas generasi.
Produk Ultra-Proses dan Risiko Gizi Lebih
Temuan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan 45% dari 29 menu MBG yang dianalisis mengandung produk pangan ultra-proses tinggi gula dan lemak—seperti susu berperisa, biskuit, sereal instan, serta sosis dan nugget kemasan.
Dalih kepraktisan dan keterjangkauan harga, penggunaan makanan ini justru berisiko menggeser masalah gizi kurang menjadi gizi lebih (double burden of malnutrition). Misalnya, satu susu kotak kecil berperisa dapat mengandung gula hingga 40% dari batas konsumsi harian anak menurut standar WHO.
Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mewajibkan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Karena itu, dibutuhkan arahan tegas untuk mendorong diversifikasi pangan lokal dan penggunaan makanan olahan mandiri, agar kualitas makanan MBG lebih terjamin.
Pentingnya Pendidikan Gizi
Meski pemberian makanan sehat bermanfaat mengatasi masalah kekurangan gizi akut, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada pendidikan gizi. Masyarakat diharapkan mampu secara mandiri mencapai status gizi baik dengan pilihan diet sehat berbasis pedoman gizi seimbang dan literasi gizi yang baik, terlepas dari pemberian makanan oleh pemerintah.
Praktik negara lain seperti Brasil, India, dan Jepang (Shokuiku) membuktikan, integrasi pendidikan gizi di sekolah dan komunitas berkontribusi pada perubahan perilaku makan berkelanjutan. Karena itu, edukasi gizi dalam program MBG sangat penting, dan universitas atau institusi pendidikan gizi mesti dilibatkan dalam mendesain materi edukasi relevan. Edukasi dapat dilakukan oleh nutrisionis atau ahli gizi di SPPG saat distribusi makanan, atau diintegrasikan dalam kurikulum sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan.
Penguatan Tenaga Ahli Gizi
Implementasi seluruh langkah di atas sangat bergantung pada tenaga gizi profesional. Pemerintah harus menambah dan memeratakan ahli gizi di seluruh Indonesia, terutama dengan rencana ekspansi ribuan SPPG baru. Menanggapi kritik atas kompetensi Sarjana Gizi muda, masalah ini tidak akan muncul jika tersedia pembinaan, pelatihan berkelanjutan, dan supervisi rutin dari nutrisionis senior, seperti skema pendampingan dokter di Program Internship Dokter Indonesia (PIDI).
Pada akhirnya, jika program MBG akan terus berlanjut dan menjadi program unggulan pemerintah, investasi sumber daya pada pendidikan nutrisionis atau ahli gizi masyarakat mutlak diperlukan demi penguatan kapasitas nasional.
Terlepas dari isu-isu kritis tersebut yang masih menjadi pekerjaan rumah, program MBG layak diapresiasi dan dilanjutkan dengan pendekatan lebih efektif dan efisien. Mengingat kebaruan program ini, pemerintah—melalui Badan Gizi Nasional (BGN)—sebaiknya menyelenggarakan forum komunikasi atau konsultasi publik rutin untuk melibatkan publik dalam evaluasi dan revisi petunjuk teknis(juknis) penyelenggaraan program.
Transparansi data BGN harus digalakkan, mencakup status sertifikasi SPPG, SOP penyelenggaraan makanan, hasil monitoring dan evaluasi, serta data kasus keracunan. Keterbukaan sangat penting agar investigasi epidemiologis dapat berjalan bila outbreak infeksi saluran pencernaan terjadi di masa depan.
Pada akhirnya, jangan sampai berlaku pepatah Inggris, the road to hell is paved with good intentions—program MBG lahir dari niat mulia pemerintah, namun tanpa eksekusi cermat, dampak baiknya justru berpotensi berbalik arah. Bila pemerintah serius membenahi investasi gizi dan kesehatan anak sekolah hari ini, bukan mustahil Indonesia akan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang produktif dan berdaya saing tinggi.
Artikel ini telah tayang di Inilah.com dengan judul “Menangkis Isu Kritis Program Makan Bergizi Gratis”